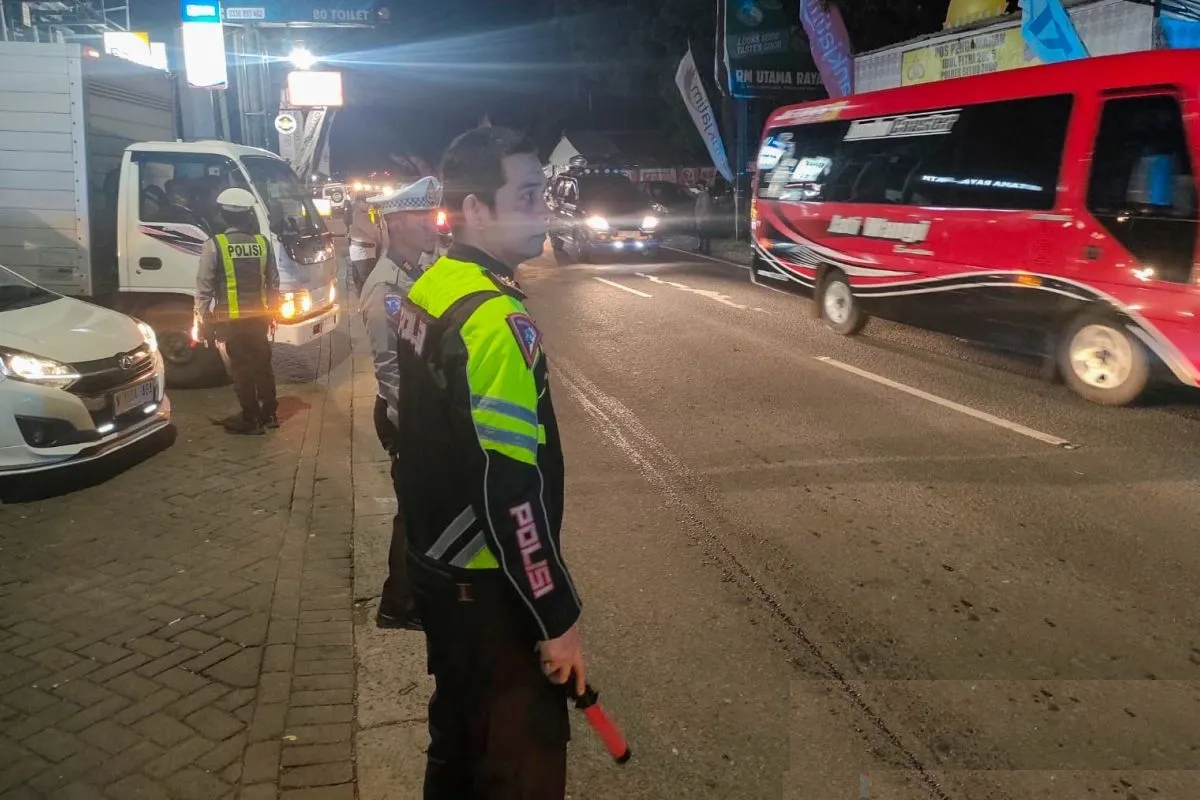Petani Mendapat Manfaat Paling Kecil dari Kenaikan Harga Beras
- World Bank
- Harga Beras
- Kesejahteraan Petani
JAKARTA - Bank Dunia baru-baru ini merilis laporan yang menyatakan bahwa harga beras di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara (Asean). Ironisnya, harga yang tinggi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Pendapatan petani di Indonesia tetap rendah. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, yang dihubungi, Minggu (22/9), mengatakan tingginya harga beras di Indonesia bukan semata-mata karena mekanisme pasar, melainkan dipicu oleh tingginya harga input pertanian.

Ket. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto - Tingginya harga beras di Indonesia bukan semata-mata karena mekanisme pasar, melainkan dipicu oleh tingginya harga input pertanian
Doc: ANTARA/DEDHEZ ANGGARA"Biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pupuk dan sarana produksi lainnya, menambah beban petani sehingga kesejahteraan mereka tidak kunjung membaik, meski harga beras di pasaran tinggi," kata Dwijono. Intervensi pemerintah misalnya melalui pupuk subsidi nyatanya tidak efektif dalam pembagiannya. "Subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah saat ini disalurkan melalui pabrik pupuk, namun harga pupuk yang sampai ke tangan petani masih di atas harga subsidi," jelas Dwijono.
Sebab itu, perlu meninjau kembali mekanisme sistem distribusi subsidi pupuk. "Sudah saatnya pemerintah mengubah mekanisme subsidi pupuk dari yang sebelumnya dialirkan ke pabrik pupuk menjadi subsidi langsung ke petani. Ini akan memastikan bahwa petani benar-benar mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut dan bisa menurunkan biaya produksi mereka," tambahnya. Selain pupuk, Dwijono juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur, terutama saluran irigasi.
"Saat ini, iuran irigasi bagi petani sudah cukup mahal, namun sayangnya, kualitas aliran irigasi yang sampai ke lahan pertanian masih belum memadai," ungkapnya. Kurangnya pasokan air yang memadai untuk lahan pertanian menyebabkan produktivitas petani sulit meningkat. Dia pun menyarankan pemerintah agar segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas irigasi. "Tanpa aliran air yang baik, mustahil produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara optimal.
Alhasil, petani terjebak dalam siklus produksi rendah dan pendapatan minim," jelasnya. Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, FX. Sugiyanto, mengimbau agar kebijakan pangan kembali mengacu pada UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Menurut dia, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah secara total kebijakan pangan di Indonesia dengan menjadikan impor pangan sebagai bagian integral dalam penyediaan pangan.
Akibanya, posisi petani sebagai produsen pangan selalu dirugikan. Dalam UU 18 Tahun 2012 disebutkan ketersediaan pangan ialah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, sedangkan impor dilakukan apabila kedua sumber utama tidak bisa memenuhi. Sementara dalam UU 11/2020 ketersediaan pangan ialah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor pangan.
"Jadi sekarang, impor pangan menjadi bagian integral dalam kebijakan pangan kita. Makanya menurut saya, harus diubah ke aturan lama karena kebijakan pangan akan menjadi ajang pemburuan rente melalui kuota impor," tegas Sugiyanto. Selain itu, dia meminta pemerintah membuat peta jalan kebijakan pangan nasional, agar ketersediaan pangan yang cukup harus linear dengan kesejahteraan produsen pangan.
Anda mungkin tertarik:
Daya Tawar Lemah
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengakui kalau bargaining position (daya tawar) petani sebagai produsen pangan di Indonesia lemah. Hal itu terlihat pada rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang sangat jarang berada di level ideal yaitu 120. NTP sendiri merupakan angka perbandingan antar Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) dan dinyatakan dalam persentase.
Bila angka NTP lebih besar dari 100, maka kondisi petani sedang mengalami surplus, sedangkan bila kurang dari 100 artinya petani mengalami defisit. "Jika harga beras naik, tapi pendapatan petani tetap rendah menunjukkan petani mendapat economic benefit paling rendah dibandingkan aktor lainnya di rantai pasok beras," tegas Esther. Fenomena itu terjadi untuk setiap komoditas pangan, bahwa petani selalu mendapat economic benefit paling kecil dibandingkan aktor aktor lain di rantai pasok.
Dia menuturkan ada beberapa hal yang mempengaruhi harga beras, pertama, kondisi supply dan demand, ketika permintaan tinggi atau tetap, tetapi supply kurang maka cenderung naik harganya. Kedua, biaya produksi yang lebih mahal, dan ketiga, biaya distribusi yang lebih mahal karena rantai pasok lebih panjang dan tidak efisien. Untuk kasus di Indonesia, berlaku tiga faktor ini menyebabkan harga beras lebih mahal di Indonesia.
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan rendahnya pendapatan petani terutama dipengaruhi skala usaha tani yang kecil. "Sebenarnya produktivitas per luasan lahan dan produktivitas petani kita cukup bagus, tetapi karena skala usaha tani yang kecil ini, pendapatan petani rendah. "Lahan yang kecil juga berpengaruh pada relatif tingginya biaya produksi," kata Qomar.
Di awal pemerintahan Jokowi, petani sebenarnya berharap banyak pada pemerintah, bisa menjalankan reforma agraria dengan mendistribusikan sembilan juta hektare lahan sesuai yang dijanjikan. "Dengan pengelolaan lahan yang cukup, akan bisa menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani," pungkas Qomar.