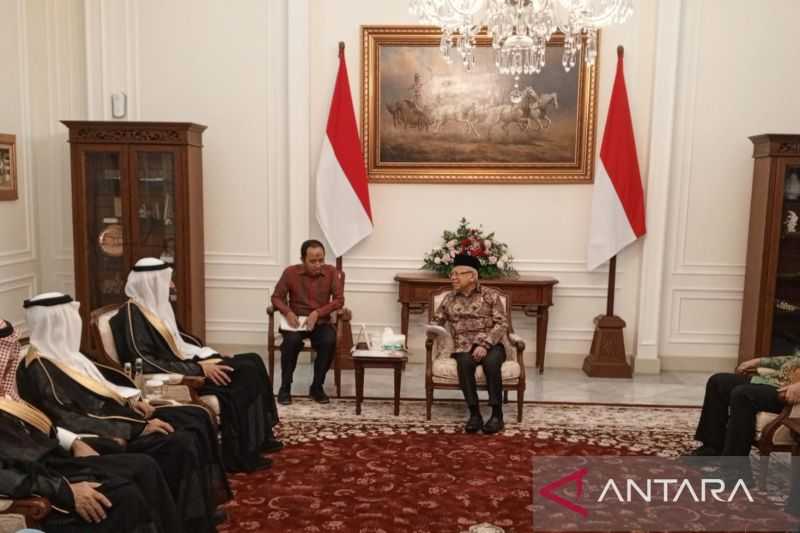Rakyat di daerah ingin maju, tapi tanpa listrik yang stabil dan cukup tidak mungkin mereka bisa mencapai impiannya.
JAKARTA - Hasil riset Global Alliance On Health And Pollution (GAHP) yang dipublikasikan beberapa waktu lalu menyebutkan, Indonesia menjadi negara keempat penyumbang kematian terbesar akibat polusi.
Riset tersebut mencatat ada 232,9 ribu kematian di Indonesia akibat polusi pada 2017 dan 123,7 ribu orang meninggal akibat polusi udara. Sedangkan secara global, polusi udara menyumbang 40 persen kematian, dengan angka kematian 3,4 juta pada 2017.
Menyadari ancaman tersebut, Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global terbesar bertekad terlibat dalam berbagai kesepakatan untuk menghadapi perubahan iklim (climate change) termasuk sebagai penandatangan Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Indonesia juga dituntut menindaklanjuti kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke- 15 (COP-15) di Copenhagen, Denmark, untuk menurunkan emisi GRK sebagaimana komitmen pemerintah dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan bisa mencapai 41 persen jika mendapat bantuan internasional pada 2020.
Namun demikian, komitmen Indonesia mulai diragukan setelah laporan yang diterbitkan baru-baru ini oleh lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative berjudul Do Not Revive Coal.
Laporan tersebut menyebutkan ada lima negara yang berpotensi menyebabkan target Perjanjian Paris tidak tercapai. Komitmen negara-negara yang dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030 adalah menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celsius dan untuk mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.
Lima negara yang bakal mengancam upaya menghindari pemanasan global itu adalah Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok. Alasannya karena masih merancang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kelima negara tersebut berencana membangun 600 PLTU batu bara baru yang mencakup sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.
Kapasitas dari seluruh PLTU itu melebihi 300 gigawatt (GW) sehingga mengkhawatirkan, karena tak menghiraukan seruan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, untuk membatalkan PLTU batu bara baru. Kelima negara tercatat mengoperasikan tiga perempat PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah Tiongkok dan 12 persen adalah India.
Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara dengan kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembangkit baru sudah direncanakan untuk dibangun.
Menanggapi kondisi tersebut, pengkampanye iklim dan energi dari GreenPeace, Didit Haryo W, mengatakan salah satu kontribusi terbesar polusi udara adalah polusi yang disebabkan oleh pembakaran batu bara sebagai sumber energi, salah satu contoh adalah Jakarta, sebagai Ibu Kota yang sering mendapatkan predikat ibu kota negara dengan kualitas udara terburuk di dunia.
"Ini terjadi akibat Jakarta dikepung PLTU, dan ke depan semakin parah karena akan mulai beroperasinya PLTU baru yang ada di sekitar Ibu Kota Jakarta (radius 100 km)," tegas Didit.
"Kita tidak ingin daerah lain mengikuti jejak Jakarta yang terkepung polusi. Karena itu, transisi energi dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) sudah selayaknya segera dilakukan sesuai dengan potensi lokal yang ada. Sejauh ini, pemerintah belum serius beralih ke energi hijau dalam rangka mengurangi emisi karbon," kata Didit.

Daerah 3T
Sementara itu, Peneliti Energi Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, mengatakan pemerintah harus serius melakukan transisi energi terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dengan energi baru terbarukan (EBT). Sebab, biayanya dinilai lebih efisien dibanding dengan energi fosil. Apalagi sumbernya sangat banyak, seperti hidro dan tenaga surya karena letak Indonesia yang berada di khatulistiwa.
"Jangan faktanya diputarbalik seolah-olah biaya EBT lebih mahal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di daerah terpencil itu biayanya sekitar 31 sen dollar AS per kilowatt (Kwh), sedangkan biaya EBT hanya sekitar 15 sen dollar AS per Kwh. Matahari lebih murah, tidak butuh biaya trasportasi karena matahari sudah tersedia," kata Ferdy.
Wacana yang dikembangkan dengan BBM satu harga seolah-olah harganya lebih murah, padahal tidak menghitung subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Misalnya untuk mengangkut BBM ke pedalaman Papua menggunakan pesawat, pasti biayanya jauh lebih mahal.
Sekarang, tuturnya, di beberapa wilayah terluar mulai dikembangkan energi surya, namun belum masif. "Di Papua, Papua Barat, dan NTT harus jadi pusat perhatian untuk EBT ini karena rasio elektrifikasinya masih rendah," tegas Ferdy.
Ingin Maju
Rakyat di daerah, tambah Ferdy, juga ingin maju, tapi tanpa listrik yang stabil dan cukup, tidak mungkin mereka bisa mencapai impiannya. Nelayan di Lampung Timur misalnya, mereka suplier udang dan terasi terbesar kedua di Indonesia, tapi pendinginannya masih pakai es balok.
"Tidak masuk akal, bagaimana nelayan bisa maju kalau tidak ada cold storage. Mereka tidak bisa pakai cold storage karena listrik sering padam, kan rugi. Itu baru nelayan, belum peternakan dan industri di perdesaaan. Belum lagi bicara pendidikan, bagaimana mau sekolah online kalau tidak punya listrik, mustahil rakyat desa bisa maju," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, mengatakan pemerintah sekarang harusnya fokus pada EBT di daerah-daerah terpencil. Pemerintah harus mendorong pengembangan EBT baik dengan memberi insentif maupun subsidi agar bauran energi semakin meningkat guna mengejar target tahun 2025 dan 2030. Kalau kembali ke diesel, ini adalah kemunduran jauh.
"Masa kita mau kembali ke era pencemaran lingkungan? Diesel itu juga mahal, jadi negatifnya double yaitu pencemaran lingkungan udara dan harga juga mahal. Sebenarnya pemerintah ini berniat atau tidak mengembangkan EBT. Kalau tidak berniat ya akui saja, jangan berniat tapi ternyata tidak dilakukan. Kalau mau mencapai target EBT di 2025 sebesar 23 pesen, ya harus dilakukan sekarang. Jangan-jangan targetnya bukan tahun 2025, tapi tahun 3025 karena sampai sekarang 5 persen saja belum," kata Ferdinand.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan untuk daerah 3T yang sukar dijangkau, opsi penggunaan energi terbarukan sebenarnya lebih feasible. "Bangun PLTD akan sulit untuk delivery bahan bakar dan biaya produksi listrik akan sangat mahal," kata Fabby.
Berdasarkan perhitungan IESR, jika PLTD dengan harga minyak di level 65 dollar AS per barel, harga pembangkitan listrik diperkirakan di angka 3.500-4.000/ kWh. Sementara dengan opsi energi terbarukan diperkirakan angkanya di level 1.500-2.000 rupiah per kWh. n ers/E-9