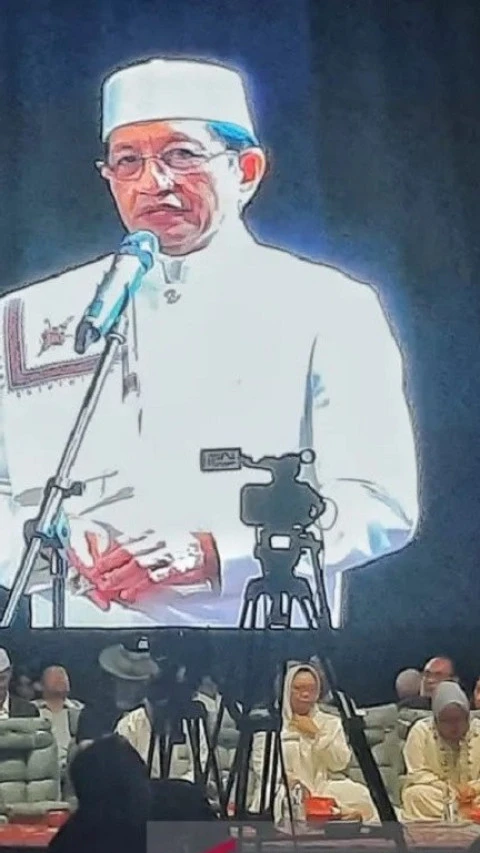Ada tiga alasan mengapa gaya aktivisme mahasiswa di Australia berbeda dengan di Indonesia, dan mengapa aktivisme mahasiswa Indonesia kian meredup.
Bagas Aditya, The University of Melbourne
Mahasiswa dan dunia pergerakan bukanlah hal baru. Mulai dari demonstrasi Tiananmen Square di Cina hingga demo 1998 di Indonesia, mahasiswa selalu menjadi garda depan dalam gerakan yang mengkritik kebijakan, menginisiasi perubahan, bahkan menumbangkan rezim pemerintahan.
Aktivisme mahasiswa telah memiliki sejarah panjang, bahkan memainkan peran dalam mendefinisikan perguruan tinggi itu sendiri.
Namun, banyak pemerhati melihat bahwa aktivisme mahasiswa di Indonesia kian melemah.
Sebagai mahasiswa yang pernah berada dalam barisan demonstrasi di Indonesia dan baru-baru ini terlibat dalam aktivisme mahasiswa di University of Melbourne (UniMelb) dalam mengkritisi isu global, khususnya terkait gerakan anti genosida dan kolonialisme modern, saya mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana aktivisme dan kebebasan berpendapat itu seharusnya dipelihara di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia.
Refleksi aktivisme mahasiswa
Setidaknya ada tiga alasan mengapa gaya aktivisme mahasiswa di Australia berbeda dengan di Indonesia, sekaligus menjelaskan mengapa aktivisme mahasiswa Indonesia kian meredup.
1. Paparan isu global
Terpaan isu menjadi kunci pembangkit gerakan aktivisme mahasiswa di kampus-kampus Australia. Sebagai universitas dengan hampir separuhnya adalah mahasiswa internasional, diskursus isu global di UniMelb sangatlah dinamis. Di kampus ini, mahasiswa berperan sebagai amplifikator dari isu yang ada di negaranya masing-masing. Misalnya, isu kekeringan di Afrika yang dikemas sebagai isu perubahan iklim, atau genosida di Palestina yang dibawa dalam diskursus penjajahan modern.
Terpaan isu global ini membuat eksistensi aktivisme mahasiswa di UniMelb menjadi dinamis dan "tidak surut isu". Ini yang membedakan dengan ekosistem aktivisme mahasiswa di Indonesia.
Rasio mahasiswa internasional di Indonesia masih sangat kecil, rata-rata kurang dari 1% dari total mahasiswa aktif. Akibatnya, dinamika isu yang menjadi perhatian mahasiswa masih seputar isu lokal, pun seringkali hanya berputar soal korupsi, kriminalisasi, dan isu-isu yang setiap tahunnya kurang lebih sama.
Terlebih lagi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menjadi representasi pergerakan mahasiswa seringkali lemah dalam membaca dinamika sosial politik, sehingga gerakan aktivisme menjadi monoton.
2. Ketersediaan ruang
Ruang untuk kebebasan berpikir kritis tak kalah penting dalam menentukan kepekaan mahasiswa pada sebuah isu. Mayoritas kampus di Australia mengizinkan berbagai pandangan politik dan ideologi untuk untuk diekspresikan atas nama kebebasan berpendapat. Pandangan sosialisme, komunisme, syariah, kapitalisme, atau demokrasi memiliki tempat untuk dipertimbangkan sebagai solusi dari persoalan yang menjadi perhatian.
Tentu ini berbeda dengan ruang aktivisme di Indonesia. Ketakutan pemerintah pada perkembangan ideologi-ideologi yang dianggap berseberangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tak jarang menjadi pagar pembatas pemikiran kritis mahasiswa. Di satu sisi, ini baik demi menjaga identitas bangsa dari serangan ideologi-ideologi yang berseberangan. Tapi di sisi lain, ketakutan yang berlebihan pada ideologi-ideologi lain membatasi sudut pandang mahasiswa dalam mengkritisi sebuah isu.
Larangan diskusi keragaman gender di beberapa kampus, misalnya, menjadi bukti bagaimana kampus dapat mengebiri kebebasan berpikir dan berdialog mengenai suatu isu sosial. Di dunia pendidikan tinggi, diskusi ideologi dan pandangan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Mahasiswa seharusnya diberi kepercayaan untuk mendiskusikannya dalam kerangka berpikir akademis.
3. Terlalu sibuk untuk 'bergerak'
Keberlanjutan motor aktivisme mahasiswa juga dipengaruhi oleh beban akademis mahasiswa. Jumlah mata kuliah yang diambil dan kegiatan kampus seperti magang menjadi hal yang sering dipertimbangkan mahasiswa saat ingin terlibat dalam aktivisme di kampus.
Belum lagi ditambah dengan pandangan publik dan dunia kerja yang masih sering mengutamakan nilai dari pengalaman aktivisme. Stresor akademis ini seringkali menyebabkan mahasiswa enggan terlibat dalam kegiatan nonakademis, termasuk aktivisme, yang dianggap menyita waktu mereka untuk belajar.
Mahasiswa di UniMelb mengambil maksimal empat mata kuliah atau 50 poin dalam satu semester. Setiap mata kuliah tersebut memiliki beban tugas dan alokasi belajar yang jelas sejak sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah. Misalnya, satu mata kuliah memiliki beban jam belajar 170 jam satu semester dengan dua tugas esai di akhir semester. Transparansi beban belajar sejak awal memungkinkan mahasiswa untuk mengukur sendiri keterlibatan di berbagai kegiatan di luar akademis.
Sistem ini berbeda dengan mayoritas kampus di Indonesia yang terkadang dalam satu semester bisa mencapai 24 SKS atau rata-rata 10 mata kuliah. Beban tugas dan jam belajar pun sering tidak terinformasikan dengan jelas.Fenomena tugas dadakan atau dosen yang tiba-tiba ganti jadwal kuliah seringkali menghambat kegiatan-kegiatan nonakademis mahasiswa.
Kurikulum pendidikan memang berperan penting dalam eksistensi gerakan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah berupaya memberi ruang bagi mahasiswa membagi kewajiban mereka sebagai pelajar dan juga penggerak perubahan. Namun, jika beban kuliah dapat diukur dengan pasti dan tidak menyita waktu, ini akan lebih mendukung mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan aktivisme.
Kurikulum perguruan tinggi perlu memahami bahwa mahasiswa tidak hanya perlu belajar di kelas, melainkan juga melalui lingkungan di luar kelas sehingga tumbuh kepekaan terhadap isu-isu di masyarakat.
Menjaga eksistensi pergerakan mahasiswa Indonesia
Mengingat sejarah keberhasilan pergerakan mahasiswa di Indonesia, seperti demo 1998, #ReformasiDikorupsi, atau Gejayan Memanggil, eksistensi aktivisme mahasiswa masih bisa dibangkitkan kembali. Apa saja yang diperlukan?
1. Kesadaran kolektif
Sebenarnya, pihak kampus di UniMelb juga terkadang melakukan upaya penekanan pada aktivisme mahasiswa. Baru-baru ini, contohnya, mereka memata-matai protestor mahasiswa untuk menghukum tindakan protes mereka di kampus. Namun, berkat kekompakkan mahasiswa, dosen, dan staf dalam memperjuangkan ruang berpendapat, kebijakan kampus tersebut digugat.
Artinya, penciptaan ruang aktivisme bukan hanya peran mutlak dari pihak universitas sebagai lembaga pendidikan. Penting pula bagi setiap sivitas akademika untuk paham hak politik masing-masing dalam aktivisme. Menjaga marwah (kehormatan) dari aktivisme mahasiswa bukan hal yang sederhana, melainkan membutuhkan usaha dan kesadaran seluruh pihak pada pentingnya ruang untuk kritik atas persoalan-persoalan yang ada.
2. Reformasi aktivisme perguruan tinggi
Kampus-kampus di Indonesia juga perlu mereformasi aturan aktivisme mahasiswa, misalnya dengan memasukkan aktivisme ke dalam bobot satuan kredit semester (SKS) seperti yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sudah sepatutnya, gerakan mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang anarki. Sebaliknya, pemerintah dan universitas perlu melihat gerakan mahasiswa sebagai keberhasilan dalam menyiapkan generasi yang kritis.
Bagaimanapun, kita perlu menjaga aktivisme mahasiswa sebagai garda terdepan dalam mengkritisi ketidakbenaran yang terjadi di masyarakat, pemerintah, bahkan dunia.
Bagas Aditya, Research assistant, The University of Melbourne
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.