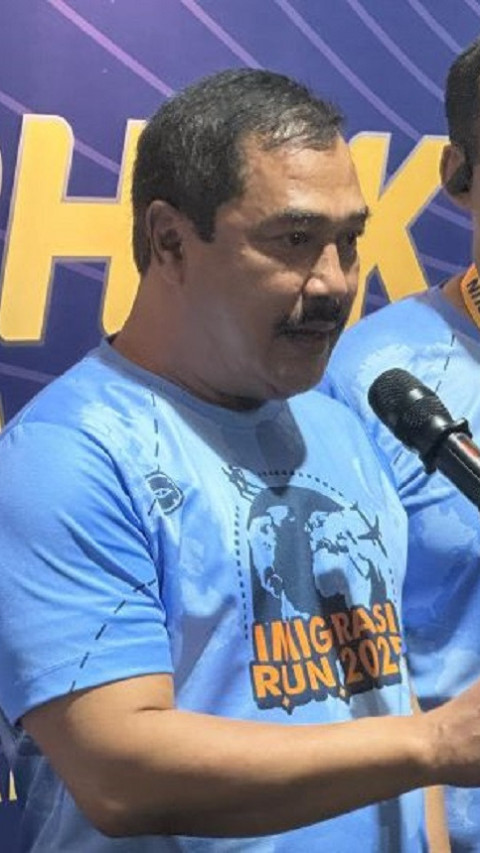Oleh: Romli Atmasasmita
Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas, LP) di Tangerang merupakan puncak masalah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Namun, itu merupakan bencana yang disebabkan oleh kelalaian petugas Lapas yang bertanggung jawab dalam masalah perawatan lapas. Peristiwa tersebut bukan sekali dua, melainkan telah terjadi beberapa tahun lalu. Masalah lain yang tengah dihadapi adalah over kapasitas yang hampir mencapai 200 persen dari kapasitas hunian lapas bukan hal yang baru, bahkan telah diakui Menteri Hukum dan HAM sejak lama, akan tetapi tampaknya solusi satu-satunya adalah membangun Lapas baru. Salah satu dari masalah Lapas adalah pembiayaan negara. Jika 0,1 persen saja dari 260 juta penduduk melakukan kejahatan dan dihukum menjadi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, sudah dapat dipastikan negara tidak akan mampu setiap dua atau tiga tahun membangun lapas.
Masalah mendasar sesungguhnya terletak pada masalah di hulu, yaitu Sistem Peradilan Pidana yang mewarisi pemikiran retributive, yaitu memasukkan sebanyak-banyaknya terpidana ke dalam Lapas dengan tujuan pertobatan atau penjeraan, sekalipun sejak tahun 1981 telah memiliki KUHAP yang baru pengganti Hukum Acara Pidana Hindia Belanda. Dampak ikutan dari sistem tersebut adalah over kapastias di Lapas. Lapas merupakan bagian hilir dari Sistem Peradilan Pidana, dan juga belum memberikan jaminan hukum dan HAM yang memadai. Sedangkan pemerintah Belanda telah mengubah 180 persen sistem hukum pidana sejak tahun 1996 di mana Undang-Undang Pidana Belanda telah melakukan perubahan orientasi sistem peradilan pidana secara mendasar, yaitu memasukkan suatu proses "transaksi" (transactie) ke dalam UU Pidana tersebut. Transaksi adalah suatu proses dalam proses peradilan pidana di mana seorang terdakwa berhak meminta penuntut umum untuk menghentikan perkaranya dan tidak melakukan penuntutan dengan alasan usia 70 tahun, kerugian telah dikembalikan, dan kerugian juga tidak terlalu signifikan (Pasal 74 a KUHP Belanda tahun 1996).
Sistem Peradilan Pidana di Belanda memperbanyak putusan pidana bersyarat dan pidana penjara hanya untuk perkara pidana yang serius seperti terorisme. Di Amerika Serikat, proses yang sama disebut injunction atau plea bargaining system, yaitu suatu negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa atau kuasa hukumnya untuk meringankan hukuman dengan cara meniadakan penuntutan atas satu atau dua kejahatan terdakwa,dengan jaminan terdakwa menyatakan dan mengakui bersalah (to plead guilty) di hadapan hakim. Di beberapa negara Eropa, tindakan hukum diskresi berdasarkan undang-undang pidana untuk sejauh mungkin mencegah terdakwa menderita di dalam penjara telah dilakukan antara lain melaksanakan pembinaan selama menghuni lapas sama seperti telah dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama ini, yaitu dengan melakukan pemisahan penempatan narapidana/warga binaan pemasyarakatan (wbp) pada tahap maksimum, medium, dan minimum security.
Lebih dari 50 tahun yang lampau, di Nusakambangan terdapat Lapas terbuka (open prison) di mana narapidana dibebaskan untuk menjalani hukuman di luar lapas dan melakukan kegiatan produktif di suatu lahan di pulau tersebut-LP Sendang Waringin. Kebebasan yang diberikan kepada narapidana/wbp tersebut ditujukan agar mempersiapkan mereka jika kelak bebas dari lapas. Namun demikian, seberapa kuatnya pemerintah melakukan pembinaan di dalam Lapas melalui kegiatan-kegiatan produktif, tetapi mengingat jumlah penduduk dan seiring dengan perkembangan kejahatan yang tidak akan pernah surut disebabkan pengaruh sosial-ekonomi di luar Lapas, perkembangan hunian Lapas tidak akan terkendali secara efisien dan memadai. Perubahan total atas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di negeri ini merupakan keniscayaan.
Perubahan tersebut dapat dipertimbangkan pemerintah dan DPR RI, antara lain perubahan tata cara peradilan KUHAP dengan cara, pertama, memperluas restorative justice sejak penyidikan, penuntutan yang telah dilaksanakan Polri dan Kejaksaan selama ini. Kedua, penjatuhan pidana bersyarat mulai dipraktikan dalam penjatuhan hukuman untuk perkara pidana, kecuali perkara pidana serius seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan lain termasuk kejahatan transnasional terorganisasi. Ketiga, meningkatkan peranan Balai Pembimbingan Sosial seperti Lembaga Parole di setiap Lapas dilengkapi dengan pendirian Pendidikan Parole dan penempatan lulusannya di kurang lebih 136 Lapas di seluruh Indonesia. Melalui perubahan-perubahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat mengatasi over kapasitas, mengurangi beban negara secara signifikan untuk biaya pemeliharaan Lapas termasuk biaya makan narapidana, dan dampak ikutannya, mencegah terjadi homoseksualitas di dalam Lapas, pemerasan, dan Lapas sebagai sekolah tinggi kejahatan.
Sepengetahuan penulis, tahun 1975-1976 penelitian di 365 LP, termasuk di Nusakambangan, keadaan Lapas tidak sebaik saat ini. Pada tahun 1975, penulis ditunjuk Menteri Kehakiman, Mochtar Kusumaatmadja, melakukan riset di LP di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Papua, dan kemudian digunakan untuk menyusun UU Pemasyarakatan dengan merujuk pada pidato pengukuhan mantan Menteri Kehakiman Alm. Dr Sahardjo. Standar yang menjadi pedoman penyusunan UU Pemasyarakatan adalah pidato tersebut dan United Nations Convention on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, 1955 dilaksanakan setiap lima tahun sekali. UU Nomor 12 Tahun 1995 telah mencabut Reglemen Kepenjaraan - Gestichten Reglement Stbl 1870. Di dalam sistem pemasyarakatan, diatur dan dilindungi hak narapidana, remisi, asimiliasi, cuti menjelang lepas dan pelepasan/pembebasan bersyarat atau invrijheidsstellingen (VI).
Perjalanan sistem peradilan pidana di Indonesia sejak kemerdekaan sudah sepatutnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap payung hukumnya -UU Nomor 8 Tahun 1981 -KUHAP maupun sub-sistem peradilan pidana, UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Peradilan Umum, dan Peradilan khusus lainya.